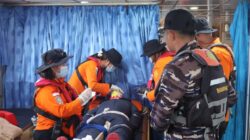Oleh: Irham Hagabean Nasution
MENJADI wartawan di Mandailing Natal sejak delapan bulan ini, saya beberapa kali ditanya warga Madina umumnya lanjut usia: anak ni Pak Muis, doho ? ( kamu anak Pak Muis ? – red).
Pertanyaan seperti ini beberapa kali saya dengar di sejumlah tempat di Madina, termasuk di Masjid Agung Nur Ala Nur, Panyabungan.
Nah, sebelum memulai tulisan ini, saya pun merenung, tercenung, menimbang ini dan itu. Sebenarnya, untuk apa menulis tentang ayah ? Untuk kepentingan apa ?
Saya kembali berpikir, hanya untuk mengagungkan keakuan ? Jangan-jangan untuk membanggakan garis keturunan ? Kesombongan sangat tak disukai Allah. Saya menjadi seperti maju-mundur, awalnya.
Alasan melanjutkan tulisan ini karena lebih dominan keinginan mengedepankan keteladanan, khususnya menjadi contoh bagi putra-putri saya, para keponakan saya, generasi saya dan setelah saya, serta mungkin siapa saja yang bisa mengambil hikmah.
Malah, saya kepingin menulis tentang ayah secara bersambung, atau bahkan sedang memikirkan untuk ditulis dalam bentuk buku. Selain diharap menjadi motivasi keteladanan, juga diharap kisah ini diungkap menjadi ladang ibadah.
Ayah saya, juga guru saya. Ayah mengedepankan kesederhanaan. Sangat pemberani. Berani menegakkan kebenaran dan keadilan, walaupun harus menghadapi berbagai tantangan.
Dia wartawan Waspada yang menjelajahi sejumlah kawasan Timur Tengah, bahkan beberapa kali tugas peliputan saat perang berkecamuk di Lebanon, Irak atau Palestina. Dia wartawan perang, penulis, pengamat Timur Tengah dan dunia Islam.
Ayah kuliah di Al-Azhar Kairo, Mesir, dengan konsentrasi mempelajari ilmu hadits. Menurut cerita ayah, perkuliahan hanya dalam cuaca dan kondisi normal.
Selebihnya, ayah ‘bertualang.’ Ayah menyebut sejumlah tempat di Afganistan, Irak, Lebanon, Sudan, Palestina, Yaman, bahkan sampai ke Belanda dan Prancis.
Saya tak tahu pasti, ayah menjadi wartawan merangkap kuliah, atau justru kuliah merangkap wartawan.
Setelah kembali di Tanah Air dalam rentang tujuh tahun, tujuh bulan dan tujuh hari [menurut hitungan ayah], dia kembali hidup ‘normal’ di Desa Gunungbarani, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailg Natal (dulu masih Tapsel).
Ayah kembali ke desa tempat ayah lahir dan dibesarkan. Ketika ayah kembali, saya sudah kelas empat SD.
Saya anak ketiga dari empat bersaudara (dua laki-laki dua perempuan). Ayah melanjutkan pendidikan berkat beasiswa di Al-Azhar Kairo, Mesir, setelah tamat dari Pesantren Musthafawiyah Purbabaru.
Ayah meninggalkan kami menuju Mesir, saat saya masih berusia dua tahun. Adek saya yang sekarang ASN di Madina masih berumur delapan bulan.
Alhamdulillah, dari empat anak ayah, tiga ASN dan saya tetap jurnalis. Ibu saya, Syamsiah AM Nasution (Allah Yarhamha), adalah sosok ibu yang sangat tangguh.
Setiba di Gunungbarani, ayah menjadi mubaligh di berbagai desa di Madina, menjadi penceramah berbagai kegiatan, termasuk perayaan hari besar Islam. Tak hanya di Madina, juga luar daerah, termasuk di Medan bahkan Aceh.
Diceritakan, ayah pernah ceramah di markas GAM, saat Aceh masih belum aman. Di Madina, sejumlah orang menyebut ayah saya ‘Tuan Mosir’ [mungkin, maksudnya Syekh Mesir, karena ayah pernah menimba ilmu di Mesir].
Selain mubaligh, ayah melanjutkan kegiatannya sebagai penulis dengan spesialisasi Timur Tengah dan dunia Islam. Sempat bertahun-tahun ayah mengasuh rubrik opini Waspada dan rubrik agama.
Persoalan berat yang saya lihat, ayah kesulitan mengaktifkan kembali status PNS (ASN), yang sudah sempat distop, setelah molor dari jadwal izin belajar untuk melanjutkan pendidikan di Al Azhar, Kairo. Ayah adalah PNS guru agama dari Departemen Agama.
Ayah mondar-mandir Madina-Medan untuk menyelesaikan persoalan ini. Dan, tak beres-beres. Sedangkan ayah terus berceramah diundang dari berbagai desa. Ayah juga menjadi guru agama di SMA Negeri Panyabungan.
Belakangan, ayah bercerita, ayah sudah tahu diikuti mobil tertentu, dengan kaca mobil berwarna gelap. Mobil ini sering terlihat saat ayah ceramah, mulai dari di desa terpencil sampai kota kecamatan. Untuk apa ? Ayah takut ? Ternyata tidak.
“Kita tidak boleh takut kalau kita tak salah,” kata ayah, yang sampai hari ini saya amalkan. Sebagai mubaligh, ayah terus melakukan ceramah, hingga suatu waktu sejumlah petugas berseragam datang ke rumah sederhana di Gunungbarani.
Buku-buku ayah diperiksa, yang memang terlihat lumayan banyak. Buku ayah dibawa dari Arab Saudi. Setiap musim haji dititipkan melalui jamaah haji asal Madina.
Ayah juga menjadi petugas haji, yang salah satunya bertugas mencari jamaah kesasar, yang menurut ayah, jamaah haji kesasar terbanyak asal Madina (dulu Tapsel).
Sedangkan pemeriksaan buku ayah berlangsung sore sampai menjelang tengah malam. Buku ayah berbahasa Arab gundul. Apakah bisa dibaca dan dipahami ?
Yang jelas, ada buku berbahasa Indonesia tentang komando jihad, mereka amankan. Saya lupa judulnya, tapi yang jelas, buku ini ayah beli di Medan, di Gramedia.
Seorang petugas meminta jaket ayah berwarna hijau bercorak tentara. Ayah langsung menolak. Bukan karena jaket dibeli ayah di Belanda, tapi, menurut ayah, wajib hukumnya mempertahankan hak.
Selesai pemeriksaan buku ayah, sejumlah buku dikumpulkan dan dibawa. Ayah kemudian ikut dibawa ke Medan untuk proses lebih lanjut. Secara pribadi, saya terlalu kecil untuk mampu mengetahui persoalan sebenarnya.
Tangis sesunggukan pun terdengar. Setelah kami berpisah tujuh tahun lebih dan nikmat pertemuan yang rasanya baru sesaat, seperti dirampas paksa.
Belakangan saya tahu, Komando Jihad adalah kelompok ekstrimis Islam Indonesia 1968 sampai dibubarkan melalui aksi pembersihan oleh anggota intelijen pertengahan 1980-an.
Penelusuran saya lakukan, sebelum ayah ‘dijemput’, pesawat DC 9 milik maskapai Garuda Indonesia dikenal dengan sebutan “Woyla” dibajak sekelompok orang mengaku Komando Jihad.
Dikutip dari Kompas, pembajakan dilakukan 28 Maret 1981 ketika pesawat memasuki wilayah udara antara Palembang-Medan pukul 10.10.
Pesawat Garuda Indonesia “Woyla” saat itu dalam perjalanan Jakarta-Medan. Namun, akibat adanya aksi pembajakan, pesawat diterbangkan hingga ke Malaysia bahkan Thailand.
Pesawat nomor penerbangan GA 206 membawa 48 penumpang dan lima awak di dalam pesawat. Sedangkan 33 orang terbang dari Jakarta, dan sisanya baru naik saat pesawat transit di Palembang. Beberapa waktu kemudian, diketahui: pembajak berjumlah lima orang.
Inilah yang dibicarakan saat ayah ‘dijemput’. Ini jadi perbincangan, termasuk di lopo-lopo. Dengan nada prihatin, banyak warga memprediksi, ayah tidak akan pulang lagi. Membicarakan ini selalu dengan tangisan.
Satu hari, dua hari, sampai tujuh hari, masyarakat dan keluarga semakin khawatir. Sepuluh hari ayah belum pulang, pengharapan pun makin menipis.
Namun, pada hari keempatbelas, ketika ayah sudah sampai di Gunungbarani dalam keadaan sehat wal afiat, masyarakat dan keluarga sujud syukur. Alhamdulillah.
Dalam rentang dua pekan, ayah ngapain dan diapain aja ? Itulah pertanyaan saya. Kata ayah, dia tidak diapa-apain, malah nginap di ruang kerja pimpinan. Kok ?
Bahkan, kata ayah, ayah mau ‘diperiksa’ kalau orangnya paham dengan apa yang dibicarakan. Orangnya pun, setelah beberapa hari, orangnya sampai di Medan dari Jakarta. Mereka pun dialog.
Selesai perbincangan ini, ayah diminta ‘sang pemeriksa’ supaya dibicarakan dalam bentuk tertulis sebagai laporan.
“Dalam satu hari sampai menjelang subuh, ayah menulis dalam 54 lembar ukuran folio,” kata ayah, waktu itu. Perbincangan dalam bentuk tertulis ini disampaikan ke Jakarta.
Gayung bersambut. Dari awal, ayah mengatakan, memang tak takut karena merasa tak bersalah. Alhamdulillah, semua selesai. Ada sejumlah tawaran, ayah menolak.
Ketika hendak pulang ke Gunungbarani, bahkan hampir berpisah, ayah kembali mendapat tawaran. Ayah kemudian mengeluhkan status PNS yang sudah dinonaktifkan.
“Alhamdulillah, itulah hikmah ayah bertemu dengan mereka. Semua menjadi mudah. Itu dimudahkan Allah. Itu semua bantuan Allah,” ujar ayah.
Ayah aktif kembali menjadi PNS dan menduduki jabatan tertentu di Kantor Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara, di Medan. Sore selesai kerja di Kanwil Depagsu, ayah menyiapkan pekerjaan di kantor Harian Waspada.
Di tengah kesibukan seperti itu, aktivitas dakwah tetap dilanjutkan sebagai ustadz. Ayah sempat menjadi salah satu pengurus di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara.
Ayah, Abdul Muis Nasution, lahir di Desa Gunungbarani, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal 17 Agustus 1941, meninggal dunia di Medan 8 Mei 2003.
Menurut saya, perjalanan hidup almarhum sangat berwarna, banyak dipengaruhi prinsip Waspada yang ditempa sangat kuat lewat dua pendiri media sangat berpengaruh: Haji Mohammad Said [Allah Yarhamhu] dan Bunda Hj Ani Idrus [Allah Yarhamha].
Dari penuturan ayah dengan nada sangat bangga, berkomunikasi pertama dengan Mohammad Said [pahlawan, tokoh pers nasional, sejarawan] saat masih menjadi guru agama sekolah madrasah di Aekdakka, Barus, daerah yang bukan homogen.
Saat itu, ayah berkomunikasi terkait tulisan ayah deretan kuburan tua di Desa Aekdakka. Di situlah kompleks Makam Mahligai. Dari siniulah kisah asal-muasal ayah menjadi keluarga besar Waspada.
Saya mohon dimaafkan kesalahan ayah, disengaja atau tidak. Kita hadiahkan kepada orangtua kita yang sekarang berada di haribaan-Nya, guru kita, kerabat kita, sahabat kita dan kaum muslimin. Alfatiha… (Penulis wartawan waspada.id dan beritasore.co.id di Mandailing Natal)